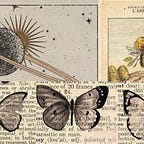Kesedihanku adalah suatu yang rapuh — lelah, terinjak, pedih, dan busuk yang mengetuk pintuku pada suatu Senin sore, tidak sabar saat ia berpindah dari satu kaki ke kaki yang lain. Ia menggigil di setiap tarikan nafas dan tulang-tulangnya yang rapuh bergemeretak pada pasang rusuk ke dua belas. Ia membentuk dirinya menjadi keras kepala, memaksa masuk ke dalam rumah tanpa perlu disapa ramah. Kesedihanku berjingkat-jingkat di sekitarku seiring dengan berlalunya waktu di hari Selasa. ia tersandung dari jalan, cepat dan ketakutan. Mulutnya tidak berani mengeja namaku, belum. Ia hanya bicara dalam bahasa diam. Ia kecilkan dirinya sendiri hingga muat dalam ruang bohlam kamar mandi. Ia letakkan telapak tangannya di telinga agar tak dengar tangis seseorang yang menderita.
Kesedihanku duduk di sisiku sepanjang Rabu pagi, mencoba mendorong tulang rusukku, mencoba membujukku untuk bangun. Ketika kami berbaring diam seperti kematian, ia merangkak di bawah selimut bersamaku. Ia adalah makhluk yang gelisah, berguling-guling, meninggalkan kerutan di manapun ia pergi. Aku berbaring miring dengan punggung hadap ke belakang. Aku beragak tuli saat ia ramai meneriaki. Setelah ia pergi, tempat tidur untuk dua orang masih terasa dingin saat disentuh, seakan-akan tidak ada yang pernah sudi berada di sini kecuali aku.
Kesedihanku mencuci pakaian pada Kamis malam, membiarkan pakaian-pakaian itu digantung ketika tidak ada matahari yang terlihat. Di dapur, ia bernyanyi sambil memasak telur dadar yang lembut, mengisinya dengan jamur dan keju seperti yang aku sukai. Ia bermain dengan kucing, memancing dengan ayah, atau bahkan menyeduh teh tiga belas kali celup, hafal betul bagaimana bentuk suka seseorang. Ketika duduk di kamar mandi terlalu lama, ia tidak memintaku untuk keluar. Sebagai gantinya, ia memegang payung besar di atas kepalaku, tanpa menyadari adanya lubang-lubang yang masih setia menganga yang tersebar di seluruh tubuh. Saat pundak kami basah kuyup, kami berdua berpura-pura bahwa tidak pernah terjadi apa-apa.
Kesedihanku jatuh sakit di suatu tempat di antara waktu sarapan dan makan siang pada hari Jumat. Ia menempelkan dahinya yang panas ke jendela dan melihat burung-burung terbang di sekitar. Ia batuk, batuk, dan batuk sampai aku hafal suara kekosongan di dalam paru-parunya. Jika ia merasa sangat sakit, ia mengulurkan tangannya dan meminta untuk digendong seperti seorang anak kecil. Aku tidak menurutinya. Aku tidak berani mengetahui seberapa berat beratnya. Aku belum siap untuk memikul selamanya.
Kesedihanku mencoba membuat dirinya menjadi sebuah puisi ketika kami tiba di jurang tajam di hari Sabtu dan Minggu. Aku melihat ia mencoba merajut suku katanya, mencoba membuatnya menjadi sebuah irama yang bisa bersendawa. Tapi itu hanya berupa isak tangis yang canggung dan noda-noda tinta yang terhapus. Ia hanya tahu bagaimana cara berduka. Ia tak pernah bisa menjadi sesuatu yang indah. Aku tak pernah bisa menuliskannya dalam bait-bait puisi. Jika kita mencoba saling mengungkapkan dengan kata-kata, yang tersisa hanyalah kelembapan di atas kertas yang sudah setengah sobek. Yang tersisa hanyalah gema dari sesuatu kata yang tak akan pernah ada.
Bersama-sama, satu bayangan besar terjerat dalam bayang besar yang lain. Besok, kita akan mulai kembali dari awal dengan tanya ‘bagaimana jika’ yang ujungnya hanya tuai sesal dan derita.
Ia hilang tinggal lara, ia terbang tembus langit jingga.
Kasih, ucap aku sayang selalu.